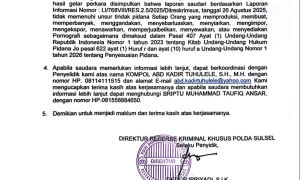Oleh Muh Nur Fajar : Alumni S2 Pendidikan Jasmani & Olahraga UNM/Atlet Hockey Sulsel
OPINI, EDUNEWS.ID – Olahraga sering kali dipahami hanya sebagai ajang kompetisi fisik dan unjuk prestasi. Namun, dalam konteks yang lebih luas, olahraga juga merupakan komoditas ekonomi-kapitalisme sekaligus arena politik yang sarat akan kepentingan.
Di Indonesia, olahraga tidak hanya identik dengan pengembangan sumber daya manusia, melainkan juga berkaitan dengan alokasi anggaran. Persoalan muncul ketika dana olahraga, yang sejatinya ditujukan untuk pembinaan atlet, sarana, dan prasarana, justru terseret dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, cita-cita luhur menjadikan olahraga sebagai medium pendidikan, kesehatan, dan persatuan bangsa kerap tereduksi oleh kepentingan sempit segelintir elite penguasa.
Komoditas
Jika ditilik dari perspektif ekonomi, olahraga termasuk dalam industri yang memiliki potensi besar. Mulai dari penyelenggaraan kompetisi, hak siar, sponsorship, hingga pariwisata olahraga, semua dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, potensi ini kerap tersandera oleh lemahnya tata kelola. Alih-alih menjadi mesin penggerak ekonomi baru, ‘komoditas’ olahraga justru sering berubah menjadi ladang bagi-bagi dana hibah, proyek infrastruktur, hingga ajang bagibagi rente politik. Kelemahan sistem pengawasan serta minimnya transparansi membuat dana besar yang dialokasikan melalui APBN maupun APBD rawan diselewengkan.
Ironisnya, pihak yang paling dirugikan dari situasi ini adalah atlet itu sendiri. Mereka sering kali menjadi korban langsung akibat dana pembinaan yang terhambat atau fasilitas yang tidak pernah selesai dibangun. Banyak atlet yang harus berlatih dengan sarana dan prasarana seadanya saja, menunggumu bonus yang tertunda, bahkan terpaksa mencari pekerjaan tambahan untuk membiayai kehidupannya.
Padahal, atlet adalah aktor utama yang mengangkat nama bangsa di panggung internasional. Ketika dana publik yang seharusnya menopang karier mereka justru dikorupsi, maka hilanglah kesempatan emas untuk membangun ekosistem olahraga yang sehat dan berkelanjutan. Pada akhirnya, prestasi atlet sering kali lahir bukan karena dukungan sistem, melainkan semangat pribadi untuk berjuang di tengah keterbatasan yang ada.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana olahraga bukanlah isu abstrak, melainkan fakta yang berulang. Misalnya, di Gianyar, dana hibah sebesar Rp 25,3 miliar yang seharusnya dialokasikan untuk pembinaan atlet justru diselewengkan hingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 3,6 miliar.
Kasus serupa terjadi di Dompu, di mana eks Ketua KONI divonis 5 tahun penjara akibat korupsi dana hibah senilai Rp 1,1 miliar. Bahkan di Makassar, tiga pengurus KONI, termasuk Ketua Umum, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi dana hibah tahun 2022–2023. Pola penyimpangan ini memperlihatkan bagaimana atlet, yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, justru dikesampingkan akibat praktik korupsi. Mereka kehilangan akses terhadap fasilitas memadai, bonus yang layak, serta program pembinaan yang konsisten.
Dalam konteks ini, kemenangan tim atau prestasi individu di arena olahraga sering kali menjadi ironi perayaan di panggung depan terjadi bersamaan dengan pengabaian dan ketidakadilan di balik layar pendanaan.
Balas Budi Politik
Olahraga di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari bagibagi – balas budi jabatan politik. Banyak jabatan dalam organisasi olahraga diisi oleh politisi, eks timses dan atau pejabat publik yang memiliki kepentingan elektoral. Akibatnya, olahraga sering dijadikan komoditas – kendaraan politik untuk mengamankan suara atau memperluas pengaruh, bukan murni untuk membina atlet.
Keterlibatan elit – politik dalam olahraga sebenarnya tidak sepenuhnya salah, sebab dukungan negara memang dibutuhkan. Namun, ketika kepentingan politik lebih dominan daripada visi pembinaan, maka olahraga menjadi rapuh dan mudah dipolitisasi. Politik anggaran, penentuan lokasi pembangunan fasilitas, hingga pembagian bonus atlet kerap diputuskan berdasarkan kalkulasi politik, bukan kebutuhan objektif.
Sayangnya, masyarakat sering terlena oleh euforia kemenangan tim atau atlet, sehingga lupa melakukan pengawasan terhadap alokasi dana olahraga. Sorak-sorai kemenangan menutupi kenyataan bahwa dana miliaran rupiah yang dikucurkan negara tidak selalu sampai pada sasaran yang tepat. Padahal, publik berhak mengetahui ke mana dana itu dikelola, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menuntut transparansi ini membuat praktik penyimpangan semakin mudah berlangsung, karena kontrol sosial yang seharusnya menjadi benteng terakhir justru kian melemah.
Sportifitas
Dalam konteks ini, integritas- sportifitas dan kejujuran seharusnya menjadi fondasi utama dalam manajemen olahraga. Tanpa nilai tersebut, sebesar apa pun dana yang digelontorkan negara hanya akan menjadi angka yang lenyap di laporan keuangan. Integritas tidak hanya dituntut dari pengurus organisasi olahraga, tetapi juga dari pejabat publik, sponsor, dan bahkan masyarakat yang berperan sebagai pengawas. Kualitas kepemimpinan yang berlandaskan integritas akan melahirkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan atlet. Sebaliknya, ketika kejujuran absen, maka olahraga hanya akan menjadi panggung kepalsuan yang merugikan semua pihak.
Keterkaitan antara olahraga, ekonomi, dan politik di Indonesia adalah kenyataan yang kompleks. Olahraga bukan sekadar panggung prestasi, tetapi juga arena perebutan sumber daya dan kekuasaan. Kasus-kasus korupsi dana hibah membuktikan bahwa tanpa integritas, potensi ekonomi olahraga hanya akan melahirkan ketidakadilan. Di titik inilah, masyarakat, akademisi, dan media memiliki peran penting untuk terus mengawal transparansi pengelolaan dana olahraga. Jika tidak, maka yang terjadi adalah siklus pengkhianatan sehingga atlet terus menjadi korban, sementara elite menikmati keuntungan dari keringat mereka.